
HIDUPKATOLIK.COM – SUATU saat saya menghadiri perayaan Sakramen Pernikahan di sebuah gereja paroki di daerah Jakarta Pusat. Memasuki halaman gereja sudah terlihat nuansa budaya Jawa karena ada hiasan janur dan ronce bunga di antaranya, yang dipasang di sebelah kiri dan kanan pintu masuk serta di depan gerbang halaman. Ada satu mobil yang baru saja menurunkan satu rombongan yang memakai busana Jawa ala Jogja. Yang lelaki memakai surjan dan blangkon yang khas, dan yang perempuan memakai kemben dan selendang di leher. Kelihatannya dari keluarga pengantin. Saya masuk gereja dan mengambil tempat duduk di tengah, sekilas memandangi dekorasi upacara yang dibuat se-Jawa mungkin. Bunga melatinya harum. Rupanya tersebar sebagian di karpet warna merah yang menuju ke altar.
Sekilas saya memandang keseluruhan ruangan gereja yang berarsitektur Neo-Ghotic khas Eropa Barat, warisan abad sembilan belas. Tampak dari ujung-ujung ruangan yang mengerucut tinggi dan mozaik kaca berwarna-warni, serta beberapa patung yang keluar dari dindingnya. Akan sempurna kalau tempat pengakuan dosanya dibuat dari kayu, menjadi semacam bilik di beberapa tempat yang menempel ke dinding. Namun ketika mata saya tertuju ke bangku-bangku yang ujungnya dihiasi ronce bunga melati dan hiasan janur di depan altar, saya tiba-tiba merasa a-morf, alias kehilangan “bentuk”. Ada dua kebudayaan besar hadir dalam satu tempat dan upacara, yakni budaya Ghotic dan Jawa. Saya bertanya kepada diri sendiri saya di mana, apakah saya tidak berada di keduanya, atau berada di kedua-duanya, atau bercampur menjadi satu identitas budaya baru yang mandiri (?).
Kecanggunan itu makin terasa ketika pengantin dan rombongan masuk ke dalam gereja dan berjalan menuju altar. Keanggunan busana pengantin Jawa dan musik pengiringnya berada dalam sebuah wadah atau ruang budaya Eropa Barat. Tempat yang tepat barangkali ada di bangunan dengan arsitektur Joglo. Ketika pengantin berada tepat di depan uskup dan dua imam yang menyambutnya, berbusana jubah liturgis yang khas Romawi, nampak dua budaya yang berhadapan dalam satu upacara keagamaan. Apakah ini akulturasi, inkulturasi, atau sekadar penyesuaian yang belum pernah sungguh-sungguh dielaborasi?
Namun ketika seluruh upacara liturgi berlangsung, nampak bahwa budaya Jawa yang ditampilkan hanya sebuah asesori, menempel di kulit depan dan belakang. Meskipun lagu Di Relung Gunung-nya (alm.) Paul Widyawan di sesi persembahan cukup menggugah perasaan kejawaan, tetapi itu hanya selintas, tidak menyatu di dalam upacara liturgi.
Mencari Legitimasi
Kejadian sederhana tersebut di atas bisa terjadi pada budaya-budaya lain di Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua di mana Gereja Katolik hadir dan berusaha untuk merangkul budaya setempat melalui banyak usaha dan percobaan. Kejadian tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana (teologi) Gereja memandang budaya dan spiritualitas yang ada di belakangnya. Apakah Gereja merasa superior di atas budaya, nilai-nilai dan spiritualitas tersebut?
Menjawab pertanyaan ini mungkin kita akan langsung melihat dokumen-dokumen Konsili Vatikan II, seperti Gaudium et Spes, Nostra Aetate, dan lain-lain, dengan spirit aggionarmentonya. Namun pendekatan tulisan ini tidak akan ke sana dan lebih kepada pendekatan budaya dan spiritualitas.
Asumsi yang sangat dasar adalah bahwa Gereja, di mana pun, selalu berada di dalam ranah budaya tertentu. Apakah itu budaya Judais atau Yahudi, Yunani, Romawi, Anglo-Saxon, Asia, Afrika, Indian, Jawa, Sumatera, Flores dan lain-lain. Tidak ada Gereja yang keberadaannya di awang-awang. Muskil. Narasi bahwa umat Gereja adalah warga dunia cukup mengada-ada dan tidak berdasarkan kenyataan. David Power dalam tulisannya Cultural Encounter and Religious Expression (New York: A Crossroad Book, The Seabury Press, 1977) mengatakan bahwa selain dari zaman permulaan Israel, Kristianitas selalu merupakan iman yang datang dari luar setting budaya di mana Kristianitas muncul pertama kali.
Kristianitas selalu berada, kemudian, dalam pakaian budaya tertentu dan asing, dan oleh karena itu mengapa Kristianitas senantiasa berhadapan dengan permasalahan budaya. Bungkus budaya Yahudi yang kemudian diambil oleh budaya Romawi (di mana kekaisaran Romawi pada waktu itu terpecah menjadi kekaisaaran Barat – Roma – dan Timur – Konstatinopel) serta daratan Inggris yang kemudian membebaskan diri dari Roma, memberi alur terjemahan Injil Sinoptik dari waktu ke waktu.
Tidak mengherankan kalau dalam kurun waktu tertentu, orang Jawa yang masuk Katolik dikatain mlebu agamane wong Londo, maksudnya masuk agamanya orang Belanda, dibaptis dengan nama-nama santo-santa yang kebanyakan berasal dari Eropa. Maka agak lucu juga kalau melihat perpaduan nama misalnya Eugenius Partoredjo. Namun selaras dengan janji keselamatan, penambahan nama baptis itu suatu kebanggaan.
Adopsi budaya lokal oleh Gereja itu sebenarnya sudah biasa dan sudah mulai dari awal kekristenan. Yang terkenal adalah adopsi tanggal hari raya Natal yang diadopsi dari budaya daratan Eropa. Tradisi-tradisi dalam Gereja Katolik lebih kurang adalah adopsi budaya lokal yang hidup yang tidak tertulis dalam Sinoptik, seperti misalnya Veronika yang mengusap wajah Yesus saat memanggul salib.
Tradisi membuat gua Natal yang muncul di Abad Pertengahan di Assisi, Italia, dari Fransiskus Assisi, yang kemudian menjadi kebiasaan umat Katolik seluruh dunia bisa disebut adopsi budaya atau kebiasaan lokal. Demikian halnya tradisi Santa Klaus, menghias pohon cemara di hari Natal, doa rosario dan lain-lain. Bisa dilihat juga cara kita berdoa pada waktu merayakan liturgi di Gereja. Tradisi berdoa sambil berdiri adalah kebiasaan berdoa orang-orang Yahudi, dan terutama dilakukan oleh kaum Parisi.

Dalam konteks ini sebenarnya kebudayaan-kebudayaan lain mempunyai legitimasi untuk diadopsi menjadi unsur, bagian, atau kebiasaan Gereja, termasuk kebudayaan Indonesia yang beragam. Misalnya sikap menyembah dengan mengatupkan kedua tangan di depan dahi pada saat konsekrasi, hal itu perlu dipertahankan untuk upacara liturgi di Jawa karena sesuai dengan kebudayaan Jawa. Legitimasi kedua datang dari sebuah pertanyaan, apakah keselamatan yang dibawa oleh Yesus hanya diperuntukkan atau berlaku hanya untuk bangsa Israel?
Semenjak mereka menolak Yesus, sebenarnya keselamatan itu telah menjadi milik bangsa-bangsa lain di luar Israel. Apakah bangsa Asia dengan budaya dan tradisi spiritualitasnya boleh menangkap Yesus? Apakah orang Jawa dengan budaya dan tradisi spiritualitasnya boleh menangkap Yesus? Boleh tentu saja, namun sayang sekali kita tidak bisa langsung menangkap Yesus dari budaya Israel atau lebih spesifik dari budaya Yahudi aramaic. Yesus dan ajarannya telah ditangkap terlebih dahulu oleh kekaisaran Romawi yang berkuasa pada saat itu, melalui Konsili Nicea, dan dibawa ke Eropa Barat. Bercampur dengan budaya Eropa Barat selama 15 abad lebih. Melalui ekspansi kolonial dan perbudakan, kabar keselamatan yang dari Yesus orang Nazaret itu dibawa ke seluruh dunia, melalui semboyannya yang terkenal Gospel, Gold and Glory.
Tidak perlu dituliskan berapa perang yang sudah tercipta dan darah yang sudah tertumpah. Tidak dapat dilupakan adalah gerakan reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther, yang melahirkan Protestantisme dan Calvinisme dan disusul dengan yang lain-lain, sebagai sikap ketidaksepahaman atas praktik-praktik keagamaan gereja Katolik pada waktu itu, di mana menurut mereka banyak praktik-praktik yang abusive. Meskipun Gereja melakukan gerakan kontra-reformasi, yang dipelopori oleh para Jesuit, namun perpecahan itu ibarat nasi sudah menjadi bubur, sampai hari ini.
Sekilas Sejarah Implementasi
Namun misi atau zending dari para misionaris yang membonceng kolonialisme tidak di semua tempat berhasil. Di Asia, Gereja berhadapan dengan tradisi keagamaan atau spiritualitas yang jauh lebih tua seperti Hindu, Buddha, Jainisme, Shinto, Konfusianisme, Kejawen serta spiritualitas lokal lainnya. Agama dan spiritualitas ini sudah berakar dan menjadi cara hidup masyarakat Asia. Gereja yang datang dengan teologi skolastiknya untuk menyelamatkan orang Asia mengalami kendala yang tidak mudah. Formulasi dan narasi animisme, penyembah berhala, agama non wahyu bagi kepercayaan orang-orang Asia menimbulkan perdebatan teologis yang terus berlangsung.
Menurut penulis sudah selayaknya kalau Gereja di Asia melihat kembali secara kritis hubungan antara iman Kristiani dan ungkapan-ungkapan budaya yang sangat menentukan rumusan iman, sebab pada kenyataannya gereja sudah ditangkap terlebih dahulu oleh kondisi Eropa Barat, yang dinarasikan lebih maju dan menjadi pusat serta pelopor di antara kebudayaan lainnya di dunia. Apakah warna budaya Gereja yang identik dengan Barat yang “triumvalistis” mampu berdialog dengan tradisi religius dan budaya serta spiritualitas Asia?
Kegagalan dalam dialog ini akan berakibat pada kemandulan Gereja dalam menyikapi masalah-masalah riil yang muncul di kalangan masyarakat Asia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Gereja cenderung akan menarik diri dan tidak mau terlibat total dalam perjuangan rakyat di luar umat gerejanya sendiri.
Teologi Pembebasan
Di Amerika Latin misi ini mengalami ‘kegagalan’. Meskipun banyak orang dibaptis namun kenyataannya tidak membebaskan mereka dari perbudakan dan kemiskinan. Yang timbul justru kemiskinan struktural. Agama Katolik dikenal sebagai agama para budak, di mana ayat yang paling populer sebagai propaganda adalah berbahagialah orang yang miskin, karena mereka empunya Kerajaan Allah. Munculnya Teologi Pembebasan di Amerika Latin adalah fenomena baru sekaligus menjadi harapan baru bagi umat, agar iman bisa lebih menjawab pertanyaan kongkret yang muncul dari kenyataan hidup keseharian yang membebaskan.
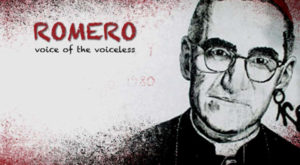
Dari sisi lain, munculnya cara berteologi ini membuktikan ketidakmampuan ajaran Gereja (Barat) menghadapi realitas budaya dan realitas sosial masyarakat Amerika Latin. Virgil Elizondo, seorang teolog Amerika Latin menuliskan bahwa dominasi Gereja Barat yang memperbudak telah banyak menyusup ke aspek kehidupan umat di dunia ketiga (lihat Condition and Criteria for Authentic Intercultural Theological Dialogue, dalam Concillium, halaman 18-19, T&T Clark, Edinburgh, 1984). Apa yang ditulis oleh David Power (sda) melihat kondisi di Amerika Latin memberi gambaran yang sangat jelas.
Menurutnya, paduan unsur-unsur agama asli dan kekristenan Portugis serta Spanyol menjadi agama para budak yang membuat mereka sungguh tunduk dan pasrah. Pelajaran yang mereka terima dari kekristenan membuat mereka tetap pada keadaannya. Paling-paling mereka dijamin keselamatan abadi jika memegang hukum-hukum moral dan religius. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa permasalahan sekaligus solusi dasar Gereja di Amerika Latin adalah kata pembebasan, sedangkan di Asia dapat dirumuskan dengan kata dialog.
Asumsi Teologis
Keselamatan manusia adalah misteri Allah dan hanya Allah sendiri yang tahu. Tak satu manusia atau sekelompok orang atau kebudayaan tertentu yang mempunyai legitimasi atas kebenaran misteri illahi tersebut. Allah, kebaikan-Nya tak terbatas dan tak dibatasi oleh peran dan usaha manusia macam apapun. Meskipun Allah telah mewahyukan diri di dalam Kristus, namun tangkapan manusia atas Kristus pun tak mampu mengungkap seluruh kebenaran atas misteri inkarnasi itu. Misteri Allah dalam Kristus yang sekarang tinggal di dalam Gereja diharapkan mampu untuk menampakkan wajah Kristus dan keselamatan universalnya.
Ada doktrin dalam Gereja Katolik yang mengatakan bahwa Kristus nampak sejauh terlihat di dalam Gereja-Nya, namun persoalan akan menjadi lain ketika pernyataan tersebut dibalik, yakni, sejauh mana Gereja saat ini menampakkan wajah Kristus? Secara khusus kita bisa bertanya: sejauh mana Gereja (di) Indonesia menampakkan wajah Kristus? Dalam konteks kebudayaan Indonesia, sejauh mana Gereja (di) Indonesia telah mampu berdialog dengan ragam kebudayaan dan spiritualitas yang ada, yang tersebar di seluruh Nusantara?
Usaha-usaha Inkulturatif
Ada banyak kearifan spiritual yang ada di kalangan masyarakat. Salah satu yang saya ingat adalah petuah dari pakdhe setiap kali keponakannya berbuat salah dan minta maaf, dia selalu mengatakan hal yang sama, “Yo wis ora apa-apa, ning ojo kok baleni yo (Ya sudah tidak apa, tapi jangan berbuat salah lagi)”. Cara ini kurang lebih sama dengan yang dikatakan Yesus kepada wanita yang telah berbuat zinah “Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang” (Yoh. 8,11). Apakah cara ini kebetulan sama atau karena didasari oleh semangat welas asih kemudian bisa menciptakan cara ungkapan yang sama?
Locus theologicus dari sebuah refleksi teologis mestinya berasal dari spiritualitas lokal dan otentik seperti ini. Saya yakin bahwa cara-cara budaya lokal yang arif banyak terdapat di dalam kebudayaan nusantara, yang merapresentasi sebuah spiritualitas tertentu di belakangnya (misalnya pela gandong, bakar batu, kerja bakti, ritual sajian untuk para leluhur dan lain-lain). Sayang di Indonesia kurang dielaborasi oleh para teolog.
Para teolog dari negara-negara lain di Asia lebih aktif untuk menggali akar budayanya sendiri dan didialogkan dengan ajaran Gereja, atau lebih tepatnya dengan ajaran Yesus dalam Injil Sinoptik. Bisa disebut teolog dari Taiwan Choan Seng Song, dengan karyanya yang fenomenal The Third Eye Theology, kemudian Aloysius Pieris, teolog India, Kozuke Koyama (Mount Fuji and Mount Sinai), Daizets T Suzuki, Hugo Enomiya Lassale, para teolog Jepang, yang banyak mengelaborasi Zen dengan kekristenan. Di Indonesia bisa disebutkan beberapa nama seperti Zoetmulder, Mangunwijaya, Hardawiryana, A. Soenarja, Kuntara W, Banawiratma, Moedji Sutrisno. Namun elaborasi itu nampak stagnan dan hasilnya sporadis. Belum menjadi sebuah gerakan.
Hasil inkulturatif secara nyata baru nampak di dalam arsitektur bangunan gereja yang mengadopsi arsitektur budaya setempat. Dan hasilnya luar biasa seperti yang saya lihat di gereja Katedral Ketapang, dan gereja-gereja di Bali. Menghadirkan bangunan candi di halaman gereja juga dilakukan di Gereja Paroki Ganjuran, Jawa Tengah. Alangkah bagusnya ketika tidak hanya tatanan luar yang diinkulturasikan namun semangat atau spirit ajaran atau spiritualitasnya. Karena kalau tidak dilakukan elaborasi keilmuan, akan terjadi a-morf, atau split of spirituality alias double standard dalam menjalankan praktek iman gereja. Ya salib ya keris.
Mirip seperti yang sudah saya singgung di atas, kemandulan atas usaha inkulturatif ini membuat Gereja kurang peka dan cenderung diam terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan budaya lokal ini, seperti jika ada perundungan terhadap budaya atau spiritualitas lain (misalnya, kasus pelarangan oleh ormas atas pembangunan makan leluhur penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Jawa Barat). Problematik kultural di Indonesia akan terus dihadapi karena keberagamannya.
Mencabut umat Gereja dari akar budaya dan spiritualitas aslinya adalah usaha yang berat, lama, kalau tidak mau dikatakan sia-sia kecuali mengartikan atau menginterpretasikannya kembali secara baru dalam terang dialog dengan iman kristiani. Usaha inkulturatif dalam pastoral dan katekese yang telah dilakukan oleh Romo Van Lith di Sendangsono, Mendut, Muntilan terbukti efektif, telah membuahkan hasil panenan yang luar biasa, dan menjadi titik balik perkembangan umat Katolik di tanah Jawa.
Usaha-usaha dialog inter-faith juga sudah dilakukan namun dalam catatan saya masih terbatas pada lapisan atas dan terbatas. Masih dalam lingkup akademis dan dalam bingkai toleransi. Diperlukan usaha-usaha untuk menerjemahkan arti dialog tersebut ke kalangan yang lebih bawah, bahkan sampai ke akar rumput. Bukan sekadar himbauan atau teori namun model-model implementasi sehingga dialog kemanusiaan dan kehidupan terjadi.
Dasar Biblisnya jelas, yakni “Sabda sudah menjadi daging” (Yoh. 1,14), Tuhan menjadi manusia. Ia yang tidak terbatas mengambil keterbatasan temporalitas manusia, dalam ruang dan kebudayaan Israel di dalam Yesus Kristus. Bela rasa Ilahi ini seharusnya menjadi bela rasa Gereja dengan lingkungan budaya dan masyarakat di mana Gereja berada saat ini. Ajer-ajur namun tetap membawa nilai keselamatan bagi jiwa-jiwa. Apakah kehadiran paroki-paroki dan umat Katolik pada umumnya di tempatnya masing-masing merupakan kehadiran menara gading, terasing, eksklusif, atau terlibat dengan keprihatinan dan kegiatan lingkungannya?
Insiatif salah satu dan satu-satunya keuskupan di Indonesia yang mencantumkan Pancasila dalam arah dan dasar keuskupannya sungguh patut diapresiasi karena semangatnya mencerminkan bahwa Gereja keuskupannya ingin terlibat dalam keprihatinan yang dialami oleh bangsa di mana Gereja berada.
Dalam konteks ini, Gereja Katolik tidak sekadar sebagai Gereja Katolik di Indonesia namun menjadi Gereja Katolik Indonesia.
RUY Pamadiken, Kontributor















