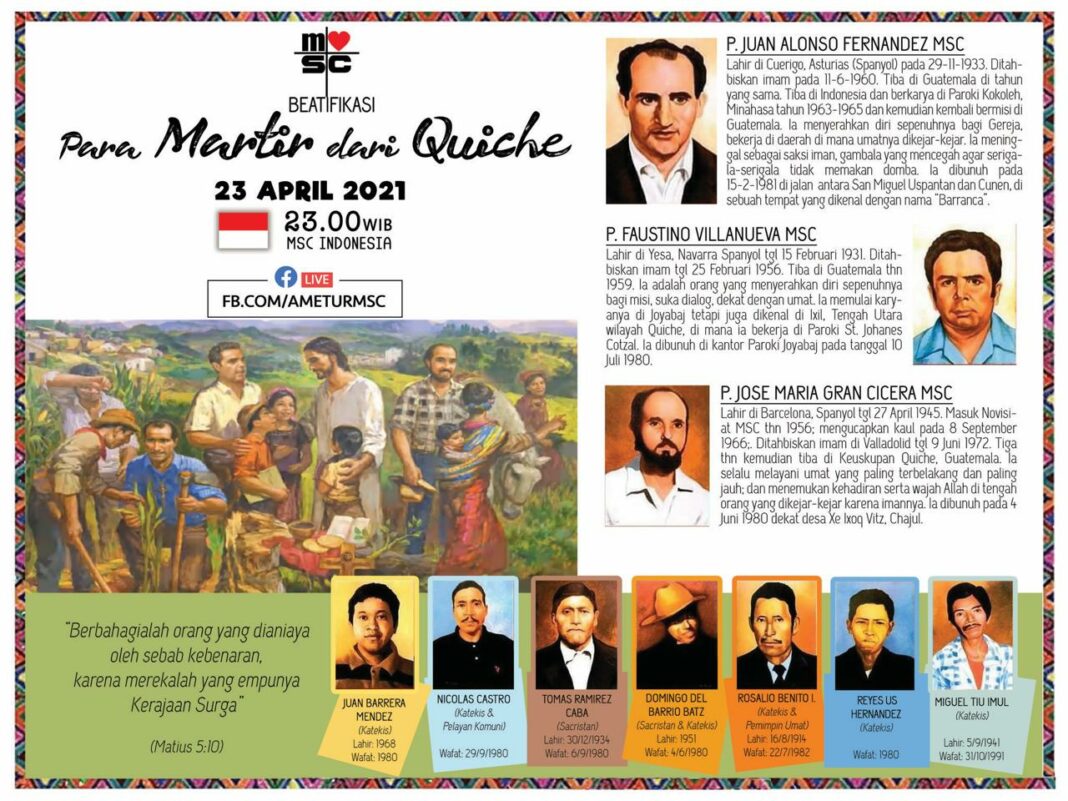MARET 1995.
Senja tampak muram. Rinai hujan yang tak kunjung reda menyempurnakan kelabu di hatiku. Sesuai pintamu, petang itu berlangsung ibadat di kediaman kita. Esok, kau dan dua rekanmu, Ulung dan Didin, hendak menuju Santiago de Chile. Tibalah saat yang dinanti-nantikan, setelah sekian lama kau memendam hasrat ingin menaklukkan puncak gunung tertinggi di benua Amerika, Aconcagua!
“Hati-hati, Karel,” pesan rekan-rekan sewaktu mereka undur diri.
Doa masih berlanjut. Sebelum merebahkan diri di peraduan, kembali kau mengajakku berdoa berdua.
“Ayo kita berdoa lagi supaya tenang,” ucapmu lirih.
Kupergoki tatapanmu lengang. Kali ini, tidak gampang bagimu meninggalkan aku dan putra kita, Matthias, yang baru berusia tujuh bulan. Lantas, kita mendaraskan doa bersama sembari menguntai genggaman. Entah mengapa, orok montok kita rewel. Berkali-kali tangisnya mengoyak keheningan malam.
“Biar aku saja yang menidurkan Matthias,” tuturmu.
“Abang butuh istirahat,” kataku mengingatkan.
Namun, tidak kau indahkan perkataanku. Di antara kantuk yang bergelayut di pelupuk mata, kutatap dirimu tengah mendekap Matthias dengan penuh kasih hingga akhirnya bayi itu terbenam dalam lelap.
Pagi masih terang tanah tatkala raungan weker menyentak aku dan dirimu dari tidur yang gelisah dan sejenak. Lalu, kita bersiap-siap menuju bandara.
“Abang harus pulang dengan selamat,” tandasku. “Anak kita masih bayi,” lanjutku di selasar rumah.
Di pelataran bandara, kau rengkuh erat tubuhku diiringi kecupan lembut yang mendarat di keningku. Meski kau beranjak dari sisiku, kehangatan dan aroma tubuhmu tertinggal di lubuk memoriku.
“Jaga anak kita baik-baik,” bisikmu dengan tatapan sendu.
“Kabari aku jika Abang sudah tiba di Santiago,” ujarku dengan suara tercekat seraya membendung air mata yang sebentar lagi tumpah.
Lantas, langkahmu berderap memasuki terminal keberangkatan. Pupil mataku membuntuti sosokmu hingga lenyap di kejauhan.
***
Aconcagua adalah mimpi panjangmu yang senantiasa menggairahkan. Sedari awal asmara kita berpagut, kau telah memancangkan tekad hendak menaklukkan gunung itu.
“Kau harus siap menjadi istri pencinta alam,” ujarmu dengan mata berbinar.
Sejatinya, setiap kali mencapai puncak gunung selalu menggoreskan makna tersendiri di hati setiap pendaki. Aku sungguh memahaminya. Target mencapai puncak Aconcagua sungguh tidak main-main! Selain membutuhkan fisik prima, juga pundi dana yang buncit. Alhasil, kau mulai menyisihkan sepeser demi sepeser perolehanmu demi menggapai impian itu kendati tonggak nafkah kita masih kerap goyah.
“Nanti, aku akan mencari sponsor,” ujarmu dengan pijar semangat.
Kutanggapi ucapanmu itu hanya dengan selengkung senyum.
Aconcagua terletak di bagian Barat Chile, tepatnya di Provinsi Mendoza. Gunung ini memiliki ketinggian 6.962 meter di atas permukaan laut (dpl); tertinggi kedua di dunia setelah Everest (8.848 meter dpl). Suhunya cenderung ekstrem hingga minus 35 derajat Celcius. Gunung yang didominasi salju, gletser, dan bebatuan basalt hitam ini memendarkan keelokan sekaligus kengerian. Di kaki Aconcagua terdapat sebuah desa kecil, Puente del Inca. Pendakian dari desa itu sampai puncak menelan waktu setidaknya tiga pekan.
Posisi gunung yang berada di antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, serta Benua Antartika membuat angin sering berputar-putar di Aconcagua. Angin putih El viento blanco yang berkecepatan lebih dari 270 kilometer per jam itulah yang menjadi momok yang mencekam bagi para pendaki. Angin yang menyerupai badai itu akan menghantam apa pun yang menghalanginya, bahkan menerbangkan lempengan-lempengan es di sekeliling gunung. Angin itu membuat Aconcagua terlihat serba putih sehingga merintangi jarak pandang para pendaki.
Munculnya angin putih senantiasa ditandai dengan terbentuknya mushroom clouds (awan cendawan) yang menakutkan. Bila menyaksikan awan cendawan, para pendaki segera tunggang-langgang mencari perlindungan. Sementara kadar oksigen di Aconcagua tipis; lebih rendah sekitar 40 persen dari pasokan oksigen di dataran rendah. Untuk tiba di puncak, para pendaki harus bertaruh nyawa melintasi beberapa pos, yakni Pos Plaza de Mulas, Pos Canada, Pos Nido de Conderas, dan Pos Berlin.
Karena sudah melahap begitu banyak korban, Aconcagua dijuluki Mountain of Death. Di kaki Aconcagua terdapat Cementerio De Los Andinistas, yaitu taman pemakaman bagi sebagian pendaki yang tak kuasa bertarung melawan kekejaman alam setempat. Nyatanya, Aconcagua tetap mempesona bagi para pendaki, tak terkecuali dirimu!
Sebagai manusia tropis, tentu tidak mudah bagimu beradaptasi dengan alam Aconcagua. Sebagai persiapan fisik, kau dan rekan-rekanmu telah melakukan serangkaian latihan intensif selama tiga bulan sebelum keberangkatan. Namun, tidak seperti pendakian-pendakian sebelumnya, kali ini bayangan dirimu bergulat menyingkirkan rintangan alam yang mahaberat lalu-lalang di benakku.
Satu purnama selepas keberangkatanmu ke Aconcagua, terjawablah kerisauanku. Kau keburu meregang nyawa di Aconcagua sebelum langkahmu menjejak puncaknya. Kau, Ulung, dan Didin tewas di lokasi yang berbeda. Jasadmu yang membeku ditemukan di ketinggian sekitar 6.400 meter dpl, tidak seberapa jauh dari puncak impianmu. Tubuhmu yang tidak bernyawa tertimbun oleh salju tebal.
“Karel dan kawan-kawan meninggal akibat hypothermia,” lapor petugas berwenang yang mengabari aku. Aku sepakat jasadmu tidak dibawa pulang ke Tanah Air. Selain karena butuh biaya sangat besar, perasaanku mengatakan bahwa kau akan bahagia menghuni Cementerio De Los Andinistas. “Biarlah tubuh Bang Karel dimakamkan di antara korban-korban Aconcagua lainnya,” tuturku di sela sedu-sedan. Kuratapi kepergianmu bak kidung lirih tanpa lirik. Liuk lekuk esok kita pun sontak terserak.
Selanjutnya, kubesarkan Matthias dengan segenap jiwa. Ia belum memahami duka yang menghempas ibunya. “Semoga suatu waktu, aku dan Matthias bisa nyekar ke pemakamanmu sembari menatap kemegahan Aconcagua,” harapku.
***
Maret 2021.
Perkabunganku telah lama usai. Telah kularung kenangan teramat getir itu ke dalam samudera waktu. Bertahun-tahun sudah kujinakkan kerinduanku padamu, sebuah kerinduan yang pedih. Terlebih, hingga saat ini aku tak kunjung menziarahi makammu. Untuk menjalani keseharian saja, aku harus pontang-panting mengais rezeki. “Bagaimana aku bisa sampai ke Chile?” gugatku.
Yang pasti, hingga hari ini aku tetap memanjatkan doa untuk kebahagiaanmu. Aku yakin, kau telah mencecap keindahan tiada tara di Nirwana Sang Khalik, yang jauh melampaui keindahan Aconcagua.
Sementara rasa syukurku kerap memuncak menatap Matthias tumbuh membanggakan. Semakin hari sosoknya semakin menyerupai dirimu. Kepekaan Matthias terhadap alam dan sesama makhluk hidup sungguh kuacungi jempol. Sedari usia dini, ia sudah tergabung dalam kepramukaan, ikut berbagai ekspedisi pencinta alam. Kerap kubayangkan, dari Surga kau tersenyum menatap jejakmu tergurat dalam diri Matthias.
“Matthias itu Karel banget,” ungkapku kepada banyak orang jika aku bertutur tentang putra tunggal kita.
Hingga hari itu tiba…
Matthias menyodorkan kejutan bagiku.
“Ma, aku mendapat sponsor untuk berangkat ke Chile. Aku ingin sekali mewujudkan cita-cita Papa yang belum tercapai; menaklukkan puncak Aconcagua,” bebernya dengan paras ceria.
Seketika aku tersadar. “Bukankah namanya memang diambil dari nama Matthias Zurbriggen, pendaki pertama yang berhasil menaklukkan Aconcagua pada tahun 1897?”
Sesak mendesak dadaku…
Oleh Maria Etty