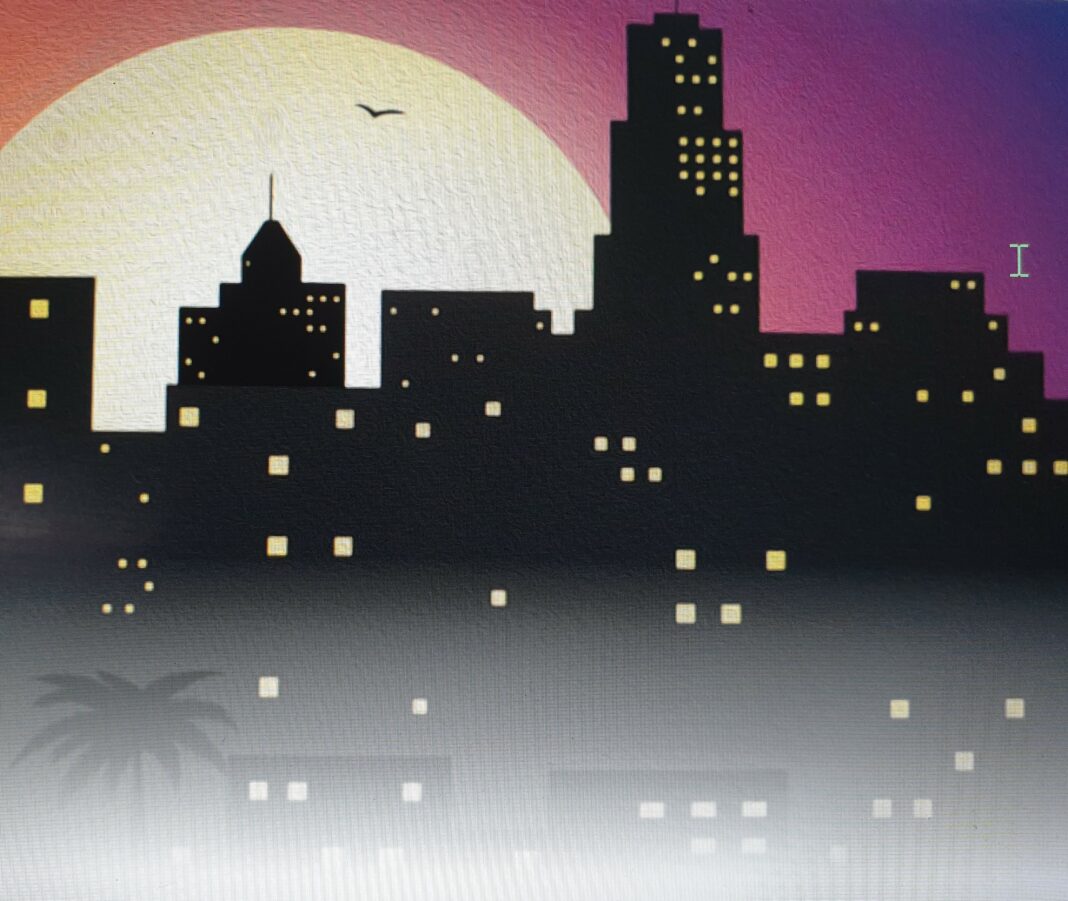HIDUPKATOLIK.COM – “Hari ini sudah laku berapa?” tanya Emily — tentu saja bukan nama sebenarnya — kepadaku. Aku mengedikkan bahu dengan jengah. Kubenahi letak dudukku dengan lebih baik.
“Mungkin ini hari sialku, Em. Tidak ada seorang pun datang, bahkan untuk sekadar menawar,” jawabku. Kunyalakan sebatang rokok, lalu mengembuskannya perlahan, membuat rangkaian asap berbentuk bulatan-bulatan di udara. Lalu lintas kota pada malam itu tampak padat. Banyak kendaraan lalu-lalang menyisakan deru mesin dan asap. Sopir-sopir dan kenek sarana transportasi darat, datang dan pergi, kadang mereka hanya sejenak, menyapa kami dengan genit, lalu pergi. Ada pula yang berhenti lama, menawar-nawar dagangan teman-temanku, lalu beli. Ah, betapa beruntung teman-temanku itu, pasti nanti pulang dengan terseok, keberatan membawa pundi-pundi rupiah.
“Sama. Hari ini punyaku juga baru laku satu. Itu pun Cuma dibayar setengah, dia bilang uangnya hilang.”
“Ah, alasan klise.”
“Hu um … licik, maunya yang gratisan mungkin. Mereka tidak paham kalau kita butuh uang.”
Malam kian larut, suara jengkerik pun seakan tenggelam dalam pekatnya. Aku pulang dengan tangan hampa. Percuma menggelar dagangan sejak sore tadi, tak seorang pun melirik. Tiada guna juga, berdandan semaksimal ini, demi memikat konsumen.
Lewat di depan sebuah warung nasi, aku berhenti. Kurogoh-rogoh kedalaman tas, berusaha mencari remahan rupiah yang barangkali masih bersembunyi. Ketemulah selembar uang biru, terpilin-pilin di antara kosmetik murahan dan wadah tisu basah.
“Syukurlah, besok mereka bisa makan,” gumamku sembari masuk warung. Kupesan lima bungkus nasi putih berlauk telur dadar dan sambal, lalu berjalan pulang. Tak jauh, hanya butuh tiga kilometer untuk mencapai rumah-tepatnya gubuk-dan bertemu anak-anak.
“Ibu kok sudah pulang?” sapa Nadin, si sulung. Gadis kecil berusia dua belas tahun itu mengambil tas plastik hitam yang kusodorkan padanya.
“Iya, hari ini dagangan tidak laku. Dah sana, panggil adik-adikmu, kita makan bersama,” ucapku. Sementara Nadin menyiapkan makan, aku menukar pakaian dengan daster yang ujungnya sudah sedikit koyak.
Selama makan, aku memandangi anak-anak itu. Nadin yang paling besar, lalu Rika yang usianya lebih muda dua tahun dari Nadin, kemudian Umar dan Rafka, dua perjaka kecil berusia nyaris sama. Mereka tampak lahap sekali makan.
“Ibu kok matanya berair?” celetuk Umar. Disentuhnya pipiku dengan tangannya yang penuh sisa-sisa nasi.
“Ssst, habiskan makanmu dulu. Ibu sedikit pusing tadi. Anak-anak, sehabis makan, langsung bobo ya? Besok hari Senin, kalian pasti ada upacara bendera di sekolah.”
**
Anak-anak itu tidur segera, mereka berjajar dengan rapi di atas kasur busa tipis bersarung gambar kartun yang sudah sangat kusam berukuran 160×200. Air mataku jatuh lagi. Kali ini kubiarkan menderas tanpa henti. Natal hampir tiba, tapi sampai detik ini aku belum mampu mengumpulkan uang, sekadar membelikan mereka baju-baju murahan di pasar, atau pun mengajak makan di angkringan.
Aku teringat pada beberapa tahun lewat, saat aku menemukan mereka di jalanan. Anak-anak itu terlantar tanpa satu pun orang dewasa yang bertanggung jawab. Tubuh mereka lusuh, bau debu dan matahari bercampur jadi satu.
Aku juga masih sangat ingat, ketika itu daganganku laris manis. Uang dalam kantong tasku bergerombol dengan riang, aromanya sangat harum. Dengan dada membusung, diiringi rasa sosialisme atau sok kaya, atau apalah itu, kubawa empat anak itu pulang. Kurawat dan kusekolahkan mereka di rumah singgah, sampai ada keluarganya datang menjemput. Namun hingga kini, tak seorang pun mencari keberadaan mereka, hingga tahun berganti beberapa kali.
O ya, keempat anak itu tidak bersaudara. Mereka tidak lahir dalam satu rahim yang sama, tetapi kejamnya dunia mempertemukan mereka, dan aku mengesahkan mereka menjadi kakak adik, menurut caraku sendiri.
“Ibu belum tidur?” kata Nadin mengejutkanku. Segera kuusap wajahku yang basah dengan kedua telapak tangan.
“Belum ngantuk. Ayo sana tidur, besok sekolah,” balasku cepat.
“Tapi Ibu menangis.”
“Hei, sudahlah! Kamu anak kecil tau apa? Sana tidur!” gertakku. Nadin tersentak. Mungkin dia terkejut, karena selama dia di sini, belum pernah aku berkata-kata kasar kepadanya dan adik-adiknya.
Nadin kembali ke kasur, menata letak tidurnya, lalu memejamkan mata. Aku beringsut menuju kamar mandi.
Kulepaskan seluruh pakaianku, dan berdiri menghadap cermin besar yang sengaja kupasang di situ. Kuraba-raba dadaku, lalu perut rampingku. Terakhir kuusap area bawah pusarku. Di sana, dulu ada sebuah mahkota yang sangat indah. Kata ibuku, mahkota itu harus kurawat sampai nanti ada seorang lelaki baik hati yang akan membelinya dengan harga mahal. Namun kenyataannya, sebelum lelaki baik hati itu datang, bapak tirikulah yang terlebih dahulu merampasnya. Merampas artinya, mengambil dengan gratis. Ibu bohong, lelaki baik hati itu hanya ada dalam dongeng.
Setelah mahkota itu lenyap, bapak tiriku mengajariku berdagang tanpa susah payah menggotong barang dagangan ke sana ke mari. Aku cukup membawa tubuh, membalutnya dengan pakaian seadanya. Semakin minim kain yang membalutnya, semakin mahal nilai daganganku itu. Pada mulanya, aku menderita kerugian. Tak jarang barang daganganku lecet, tapi konsumen enggan bertanggung jawab. Mereka memperlakukannya dengan sadis dan brutal.
Lambat laun, aku mulai menikmati pekerjaanku sebagai pedagang. Tubuhku acap berdenyut, kelojotan dengan liar, jika sehari saja aku libur. Napsuku kian tak terkendali. Terutama soal uang. Uang yang tidak hanya untukku menyambung kehidupan, tetapi juga untuk anak-anak itu.
Sejak dua hari terakhir, tubuh bagian bawahku mengeluarkan cairan putih berbau busuk. Aku tahu, itulah yang menyebabkan daganganku tak laku lagi. Pasti para lelaki hidung belang itu menjauhiku karena tahu aku mengidap penyakit.
Suasana Natal sudah mulai tampak di setiap sudut kota. Pernak-pernik hiasan dan lampu, menyemarakkan wajahnya. Lagu-lagu ceria tentang kelahiran Sang Juru Selamat pun terdengar begitu indah.
Kakiku berhenti melangkah, tepat di depan sebuah kapel tua yang terlihat begitu sakral, mungkin karena usia bangunannya, atau juga dari detail ornamen Natal yang dihiaskan begitu agung dan sederhana. Banyak orang mulai datang ke situ, berpakaian rapi dan membawa buku Madah Bakti.
“Ada Misa?” tanyaku pada seorang bapak.
“Hari ini pastor melayani kami untuk pengakuan dosa,” jawabnya. Aku tertegun, sembari mengingat-ingat, kapan terakhir aku mengaku dosa. Baru saja dua langkah, kunaiki anak tangga di depan pintu masuk kapel itu, hatiku bergetar. Masih bolehkah aku datang, Tuhan? Menyapa-Mu dalam kekosongan imanku ini?
Kuurungkan niat untuk masuk dan menerima Sakramen Pengakuan Dosa, merasa belum pantas di hadapan-Nya. Jubahku hitam, penuh noda berbau busuk di sana-sini. Samar, tapi berlafal jelas, kudengar bisikan, “Anak-Ku, kemarilah.”
Rembulan di atas kota tertutup awan, sinarnya tak jelas, kadang temaram, kadang benderang. Aku mulai ketakutan, anak-anakku tak dapat menikmati hangat suasana Natal.
Oleh Genoveva Dian Uning