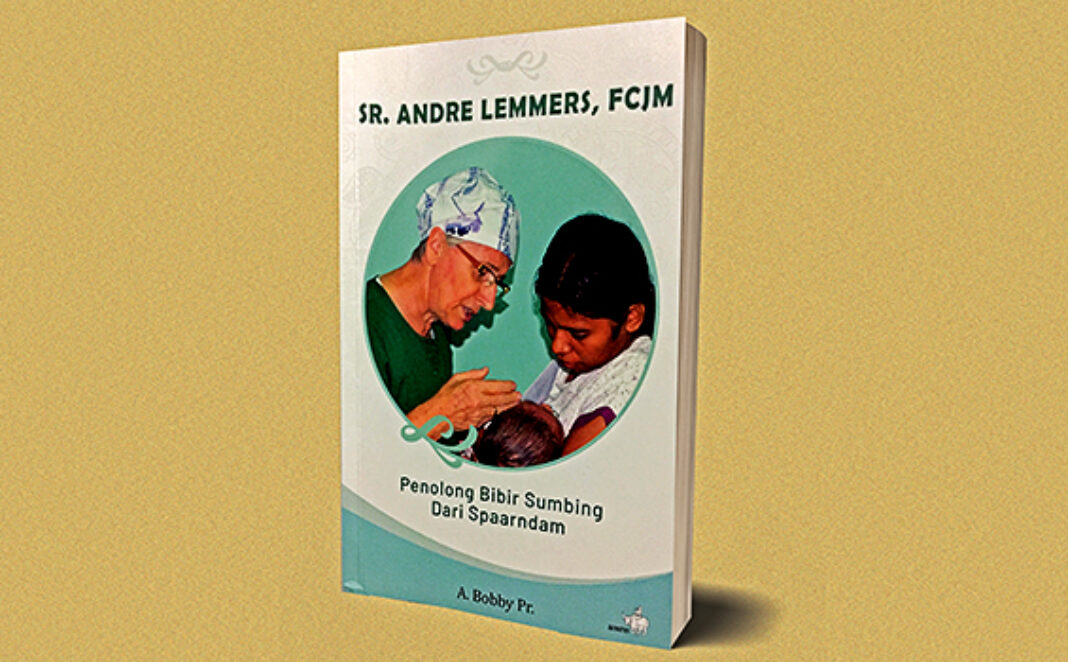HIDUPKATOLIK.com – Pagi-pagi benar, terdengar suara sorai senang. Ekspresi teman-teman sekolah sungguh membahagiakan. Penasaran. Aku berlari meraih finis. Di papan pengumuman telah tepampang hasil kelulusan siswa. Aku menghela nafas melihat urutan namaku. Syukur, hasilnya memuaskan. Ceria. Di balik itu, aku tenggelam dalam kegelisahan. Ini terkait masa depan.
Tinggal di asrama bersama para biarawati selama 3 tahun cukup membuat aku mengagumi mereka. Sebenarnya, niat itu sudah tersusun rapi dalam benakku. Sayangnya, itu sesuatu yang mustahil. Saya berasal dari agama Protestan. Mimpi itu hanya kubisikan kepada seorang suster. Takut dan malu keluarga menolak dan membenci aku. Nasihat-nasihat yang diberi suster itu menjadi obat ketakutanku. Ia tidak mengikatku tetapi mengajak aku untuk terbuka kepada orang tua.
Menjadi suster adalah mimpi masa depanku. Mimpi belum tentu 100% akan nyata. Mimpi itu tidak pernah kubicarakan karena sikap marah ayah membuatku frustrasi. Sikap diamku, seolah mengasingkan diri. Padahal cinta mereka selalu terpancar untukku, baik waktu di asrama pun setelah tinggal di rumah. Kira-kira sebulan saya tinggal di rumah terhitung awal Mei. Memasak, membersihkan rumah, mencuci dan sebagainya bukan sesuatu yang asing lagi. Pengalaman di asrama kini semakin nyata. Sejak di rumah, saya sudah banyak melayani tamu. Tamu adalah berkat bagi kami.
Malam telah menyelimuti bumi, alam telah membisu namun suara tamu masih tersiar nyaring, membuatku tak bisa tidur. Walau tubuh kelelahan, aku bangkit berjalan ke arah pintu kamarku. Tepat di dekat pintu aku berhenti. Aku membungkuk sambil mengintip lewat lubang kunci. Objek tak jelas dan kabur. Pastinya, tamu itu ada dua orang.
***
Fajar telah menyingsing. Embun pagi masih hinggap di ujung daun bunga yang berdiam di atas meja perangku. Aku membuka jendela dan mengundang udara segar memenuhi kamar kecilku. Mataku menangkap mobil kijang yang tak asing, karena kerap datang. Aku bergegas membereskan kamarku.
Tok…tok…, pintu kamarku diketuk.
“Mia,” mama memanggil. “Tolong buat kopi untuk tamu kita, nak!”
“Iya ma,” jawabku gembira.
Entah kenapa, pagi itu hatiku riang ceria sampai gelas di atas talam hampir menjadi korban kecerobohanku. Melihat seorang tamu yang tampan membuat jantungku berdebar. Ini sesuatu yang tak kuduga. Pemuda itu duduk diapit oleh pria dan wanita yang lebih tua darinya. Mungkin, mereka orangtuanya atau abang dan kakaknya. Aku kembali menatap wajahnya. Aku menganggukkan kepala dan seulas senyum menghiasi tersungging di wajahku. Grogi.
Ayah mengundangku untuk duduk bergabung bersama mereka. Ini kesempatan bagiku untuk melihat si dia yang mempesona. Mimpi apa aku semalam? Sehingga perasaanku berbunga-bunga. Aku pun duduk. Sesekali, bola mata bergerak ke arah pemuda itu. Tiap kali aku melirik, pupilnya berkedip seakan mengirim pesan untukku. Sorotan matanya menembus sisi gelap pandanganku. Bisa jadi, dia telah merasuki jiwaku sehingga aku harus terpaksa meliriknya. Andai saja aku seorang pelamar, mungkin aku tidak berada di situ karena aku belum bisa membalas tatapan itu.
Ayah memulai pembicaraan itu dengan memperkenalkan diriku kepada ketiga tamu itu. Dua orang yang mengapit pemuda tampan itu adalah keluarganya. Sebelumnya, hanya kedua orangtua itu yang sering datang. Ayah pun selesai berbicara, kemudian berganti kepala keluarga itu yang bicara. Ia memperkenalkan diri dan mengutarakan tujuan kedatangan mereka. Inti kedatangan mereka ialah mencari tulang rusuk bagi buah hati mereka.
Jelaslah sudah, namun aku belum siap. Tidak mungkin domba bisa tenang dalam kandang gembala yang belum ia kenal. Sejenak, aku membisu. Dalam heningku tak kutemukan diksi untuk menolaknya. Tanpa banyak pikir, aku sontak berdiri. Kata maaf terlontar dari bibirku, kemudian aku berlari ke kamar. Sikapku sungguh ceroboh. Mau bagaimana lagi? Hanya itu yang bisa kulakukan. Pilu terasa dalam hatiku. Aku tak tahu harus berbuat apa. Kucoba untuk tenang. Dunia terasa sepi dan kosong. Tak ada tiang untuk bersandar dan payung untuk berlindung.
***
Hari pun berganti. Burung-burung bernyanyi menyambut sinar fajar yang menembus sela-sela pohon. Situasi alam ini membuatku terhibur. Aku merasa bahwa akulah manusia yang sempurna. Suara alam menjadi daya hingga aku dapat menyelesaikan pekerjaanku pagiku. Setelah adik-adikku berangkat ke sekolah, aku sarapan bersama dengan orangtuaku. Bersyukur adalah wujud doa kami. Dalam doa juga saya menyelipkan permohonan : semoga keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis. Beberapa menit setelah doa, saya meraih tangan mereka.
“Pa, ma…, maafkan Mia atas peristiwa kemarin,” kataku sambil melihat kearah mereka. Mereka menganggukkan kepala.
“Kami juga minta maaf karena tidak mengatakannya kepadamu terlebih dahulu,” jawab mama dengan tenang.
“Itu bukan sebuah kesalahan. Bagiku hal itu sesuatu yang mustahil terjadi. Aku belum matang. Di balik itu juga ada yang kupikirkan namun sulit untuk dijelaskan.”
“Ungkapkan saja nak,” sahut ayah penasaran.
“Sebenarnya, sa…saya ingin me… menjadi biarawati,” jawabku terbata-bata. “Aku tahu bahwa keluarga kita beragama Protestan maka mimpi itu sulit menjadi darahku. Bila parang tak diasah maka siasia kita menggunakannya. Mungkin lebih baik saya melanjutkan kuliah sambil kerja. Biaya kuliah akan saya tanggung sendiri,” kataku penuh harap.
Mendengar itu, mereka saling berpandang. Tiba-tiba mama meneteskan air mata. Ia meraih tanganku sambil berkata, “Sekali lagi, maafkan kami nak! Kesusahan senantiasa berpihak pada kita. Keadaan itu memaksa kami meminjam banyak uang kepada tetangga terutama keluarga pria itu kemarin. Kami pikir dengan menjodohkan kalian, utang kita dapat terlunaskan.”
Perih, sakit, bercampur aduk dalam lubuk hatiku. Tak pernah kubayangkan, diriku bagaikan barang tebusan. Hal ini membuat kesedihanku kembali menggunung. Makanan di mulutku menjadi pahit dalam sekejap. Air liur terasa kering hingga ke tenggorokkan. Pun air mataku tak kujung datang, semua sudah kering. Aku hanya pasrah tanpa takut. Tuhan memiliki rencana luhur untuk hidup kita.
***
Masa telah silam. Kini umurku menginjak matang. Andaikan waktu bisa diputar ke belakang, aku akan mengakhirinya dari awal. Apa yang dulu kuabaikan telah nyata. Kenapa tidak dari dulu kulihat kenyataan ini? Ini bukan takdir. Aku hanyalah pemeran di bawah kontrol Sang Waktu. Aku yakin, waktu yang sama tak akan terulang, kecuali kepastian. Pandangan hidup bukan lagi mimpi. Kepastian sedang telah menanti di pucuk akhir. Ini bukan suatu tawaran namun realita. Di balik itu Sang Waktu mengatasinya.
Allah, semoga Engkau membuka pintu kerahiman-Mu dan mengasihani mereka yang berpulang dalam damai-Mu, seruan doaku di dekat kedua batu nisan orang tuaku. Kalimat ini senantiasa kuselipkan di setiap doaku sejak mereka menghembuskan nafas titik terakhir. Mendoakan orang meninggal adalah ajaran iman katolik. Orang hidup memiliki kewajiban untuk mendoakan jiwa-jiwa orang meninggal dan juga memohon doa-doa mereka.
Penghayatan iman ini merupakan rahmat kebaikan mereka. Kalau tidak ada izin dari mereka, mungkin tidak ada kesempatan bagiku untuk menikah dengan orang Katolik. Yang menjadi permenunganku ialah: Tuhan tidak mengizinkan aku menjadi seorang biarawati namun Ia memperkenankan aku masuk agama Katolik. Kendati mimpiku tak terealisasi, semoga nyata dalam diri anak-anak kami.
Kata-kata ini, kuletakkan di atas kubur mereka saat selesai ziarah. “Semoga berkat doa mereka, Tuhan mengetuk dan membuka pintu hati anak-anak kami untuk melayani Dia,” bisik hatiku.
Silfanus Harefa
HIDUP NO.28 2019, 14 Juli 2019