HIDUPKATOLIK.com – Dari ketinggian Taman Doa aku memandangi Ambarawa-Salatiga yang dipisahkan oleh Rawa Pening. Dari kejauhan lampu berkelap-kelip menandai masih ada kehidupan di sana. Gunung Telomoyo mengintip dari kegelapan. Angin dingin bertiup kencang, aku merapatkan jaket bertudung yang menjadi pelindungku dari terpaan angin dingin.
Taman Doa tidak begitu ramai, hanya beberapa orang yang sekadar mampir setelah dari toilet usai khusuk berkanjang dalam doa. Bagi orang Ambarawa jam sembilam malam bukan seperti jam sembilannya orang Jakarta. Kalau aku perhatikan mereka-mereka ini bukan orang Ambarawa. Itu gaya pakaian orang Jakarta. Celana pendek bersepatu, yang cewek celana pendeknya makin pendek. Tangannya selalu memegang HP dan powerbank, kabel bersliweran dari HP ke telinga. Dan setiap gerak diambil gambarnya lalu upload. Masih juga selalu kelihatan sibuk dengan medsos. Kasihan Bunda Maria yang hanya sekadar menjadi background foto.
Malam-malam seperti ini selalu aku rindu. Dingin, sepi, dan sendirian. Meski sudah tahun ketiga aku di sini, aku belum mengenal banyak orang. Hanya beberapa orang guru dan karyawan serta orang tua saja. Orang banyak belum mengenal dan aku belum mengenal mereka. Waktu memperkenalkan diri, aku minta mereka memanggilku Suster Francis yang diambil dari Franciska. Anak-anak memanggilku Suster Pransis atau Suster saja. Jaket tebal bertudung menyembunyikan kesusteranku, aku dianggap sebagai peziarah yang lain, tak ada yang menandai kalau aku seorang suster. Itulah yang aku kehendaki. Mereka tidak perlu tergopoh-gopoh menyalamiku. Mereka cuek, aku pun bisa cuek.
Namun, aku tidak bisa cuek dengan jejak emosional yang membuatku harus minta pindah tugas. Jejak itu selalu mengikutiku ke mana pun aku melangkah. Gua Maria Kerep ini menjadi tempat aku menangisi dan menyesali keputusan salahku. Lima tahun tidak bisa melupakan terpaan masalah pada waktu itu. Dalam doaku, aku mohon untuk guru-guru yang telah aku zolimi dengan keputusanku agar mereka dikaruniai kemudahan dalam menafkahi keluarganya. Agar dibukakan pintu maaf bagiku.
Tak terasa malam cepat datang, tak baik seorang suster sendirian di taman, meskipun itu di taman doa.
***
Jakarta.
Jakarta merupakan pusat segalanya. Ada perasaan bangga yang membuncah ketika ditempatkan di Jakarta. Tidak sia-sia meski tertatih-tatih, kuliah demi kuliah berhasil kuselesaikan. Aku sungguh sadari hanya ketekunan dan doa yang membuatku bisa mengenakan toga dua kali. Aku hanyalah cah ndeso. Aku taklukan ibukota, Jakarta.
Jakarta memang membuka peluang seluas-luasnya, selebar-lebarnya bagi siapa saja, apalagi posisiku sebagai pimpinan. Aku menjadi kenal orang-orang yang berpengaruh di negeri ini, berbagai urusan dengan para pejabat di pusat dengan cepat dilakukan, relasi dengan orang-orang berduit. Sekolah yang aku pimpin memang berisi beberapa anak pejabat dan pengusaha papan atas. Semua menjadi serba lebih mudah. Mau buat kegiatan apa pasti terlaksana dan sukses.
Aku juga menjadi akrab dengan media. Ketika, Stefani meraih nilai UN tertinggi mereka datang dan mewawancarai Stefani. Aku sebagai pimpinan ikut juga diwawancarai. Ketika mengadakan kegiatan dan mengundang wartawan untuk meliput, mereka datang, apalagi beberapa orang tua murid bekerja di media.
Posisiku membuat majalah pendidikan sering memintaku untuk menulis. Awalnya aku hanya copas sana sini dan aku bumbui dengan pengalaman. Lama-lama jadi sering menulis. Iseng-iseng aku kirim juga tulisanku ke koran dan syukur dimuat, mungkin karena posisiku itu. Berkat tulisan yang dimuat aku menjadi sering diminta pula menjadi narasumber dalam seminar, lokakarya atau simposium. Aku sudah dianggap pakar pendidikan.
Aku benar-benar sibuk. Aku terbiasa makan pagi di Jakarta, makan siang di Medan, makan malam di Jakarta lagi. Terbang ke luar negeri juga biasa sesuai undangan dan kegiatan. Urusan sekolah bisa diatasi oleh rekan-rekan jajaran pimpinan. Sekolah tetap bisa berjalan tanpa kehadiranku. Para guru juga menjalankan tugas dengan baik meski tidak aku pelototi dari kelas ke kelas. Aku angkat topi untuk guru-guru ini, meskipun banyak ngomong, banyak usus, banyak protes tetapi kalau sudah sampai hari-H mereka bekerja dengan sepenuh hati. Aku jadi banyak menyerahkan berbagai urusan kepada mereka.
Sepulang dari Manila, aku mendapat laporan kalau ada sembilan guru menyampaikan protes ke pusat. Mereka terang-terangan minta supaya kepala sekolah diganti. Bahkan mereka telah mengumpulkan dana untuk membelikan tiket ke mana pun aku ditempatkan. Ini tamparan keras kepadaku. Aib. Cela. Mbalelo, Makar terhadapku, sebagai orang nomor satu di sekolah ini.
Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini sudah menginjak-injak harga diriku. Enam guru segera aku pindahkan ke tempat yang baru. Tiga guru langsung kurumahkan. Mereka ini, Emil, Karjono, dan Widi. Mereka telah menghasut teman guru lain untuk mbalelo. Aku panggil satu satu, aku berikan suratnya. Dan tidak ada dialog karena akulah pimpinannya, akulah komandannya. Selesai. Akulah pemenang perang ini. Mereka kalah.
Tahun ajaran baru tiba. Aku masih berjalan dengan membusungkan dada sebagai orang nomor satu. Ternyata mencari sembilan guru sekaligus sungguh mudah meskipun sudah dengan nama besar sekolah. Akhirnya kami berhasil mendapatkan guru baru. Namun, aku tidak mengerti kenapa mereka hanya bertahan tiga bulan, enam bulan saja. Aku mulai kelabakan. Terpaksa menerima guru yang asal mau mengajar saja, mengabaikan kemampuan dan kompetensinya.
Waktu berjalan dengan cepat. Pertama aku tak terlalu peduli ketika ada orang tua mengajukan permohonan pindah sekolah anaknya. Itu hal bisa di Jakarta ini dan diperbolehkan. Tidak ada yang bisa melarang. Itu hak orang tua dan anak, mau sekolah di mana itu pilihan logis mereka. Namun, menjadi persoalan serius kalau ada sekitar lima anak dari tiap kelas yang pindah sekolah. Pasti ada yang tidak beres.
Ketidakberesan semakin menjadi-jadi. Pendaftar jauh dari harapan, dari alokasi empat kelas hanya mendapatkan dua kelas anak baru. Itupun kelas kurus dan tanpa seleksi. Aku dipanggil pusat untuk mempertanggungjawabkan merosotnya jumlah murid. Ini berpengaruh pada keputusan pimpinan pusat, masihkan perlu mempertahankan sekolah dengan berdarah-darah atau ditutup. Aku diberi waktu tiga hari untuk menjawab dengan argumennya.
Malam-malam yang dingin, semangkuk wedang ronde menghangatkan tubuh ditemani jagung bakar keju. Ini hanya bisa terjadi di Gua Maria Kerep, tempat lain akan berbeda nuansanya. Motor Revo meluncur membawaku kembali ke biara. Eh ….. di sebelah kiri jalan …. ada rica-rica RW… yang ini juga bisa menghangatkan tubuh yang diterpa angin dingin Rawa Pening. Tapi ….. aku ragu. Mampir atau lanjut? Punya saran? WA 0857-76295603 pliiis…. keburu habis….
Nicolas Widi Wahyono
HIDUP NO.31 2019, 4 Agustus 2019






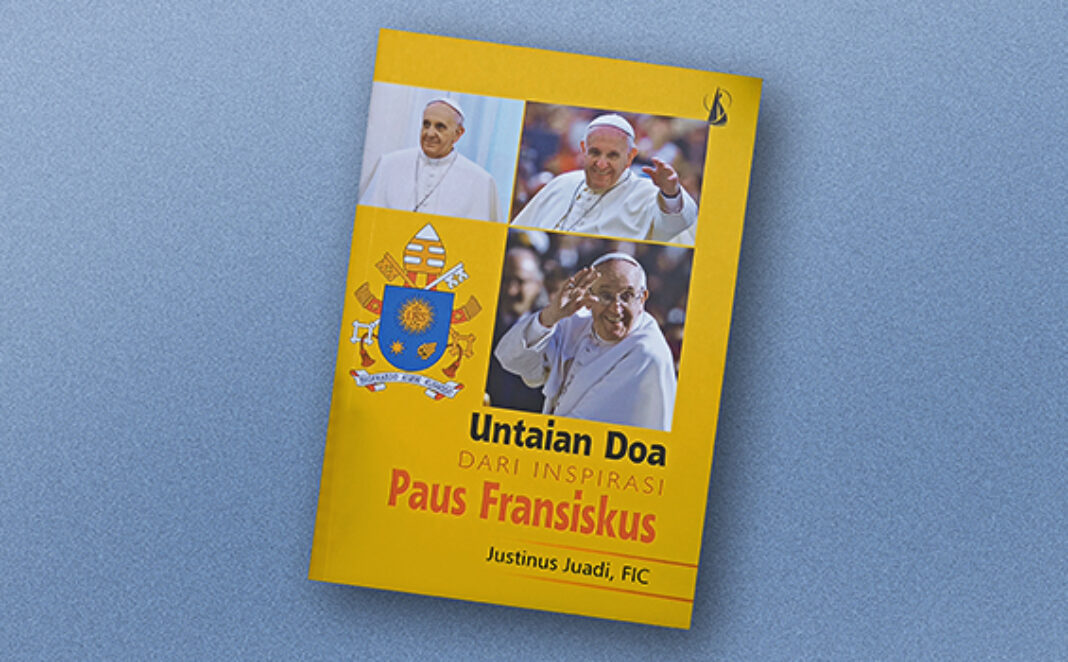
Menarik..