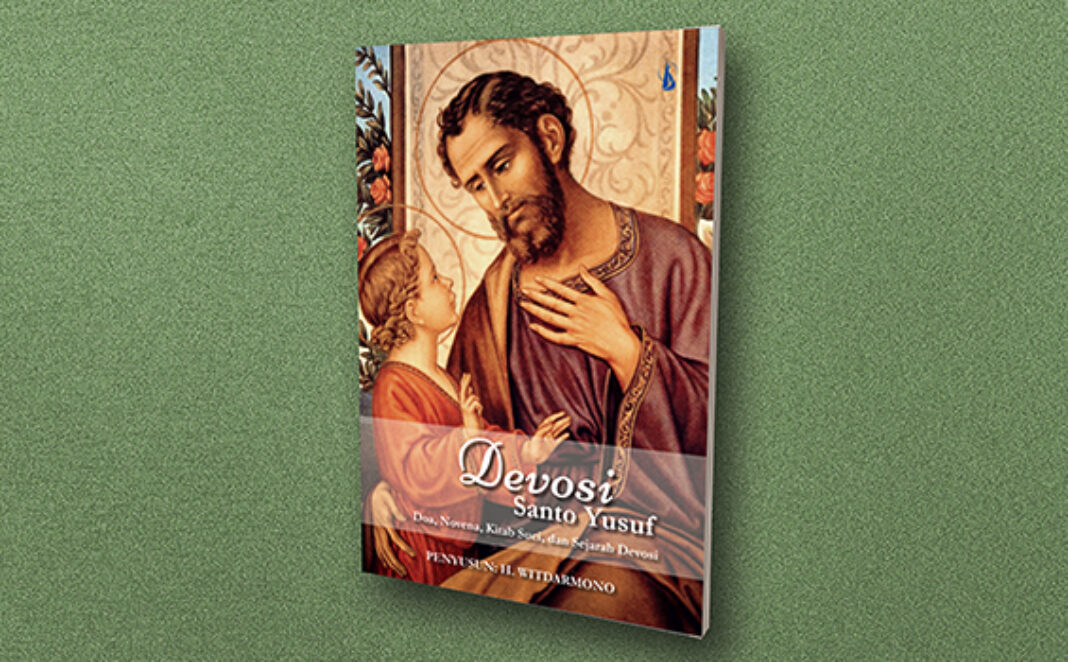HIDUPKATOLIK.com – Dengan susah-payah, jemari Oma Lina yang sudah tak lentik mengait-kaitkan benang wol dengan haakpen. Sementara tangannya rada bergetar akibat tremor. Pijar semangat oma berusia nyaris tiga perempat abad ini sungguh patut diacungi jempol.
Ada sebelas oma, termasuk Oma Lina, yang belajar merajut kepadaku. Beberapa di antara mereka berhasil membuat taplak, syal, dan sepatu bayi.
Sedari remaja, aku sudah mahir merajut guna mengisi liburan sekolah. Nyatanya, di masa senjaku, keterampilan itu bisa menjadi sarana untuk menabung kebajikan sekaligus tambahan bekal menuju akhirat kelak.
Memang aku perlu merentangkan kesabaran mendampingi para oma merajut. Namun, serta-merta ada kebahagiaan seakan itulah upahku selepas mengajari mereka membikin kerajinan tangan. Aku bahagia bisa berbagi. Berbagi dengan cara bersahaja.
“Maria, bagaimana ini kok rajutanku tidak rata?” keluh Oma Rita dengan raut masam.
“Lha, ini salah mengait. Makanya, jalurnya jadi mencong,” balasku sembari mengurai benang yang terlanjur dikait.
Tak terasa dua jam telah terlampaui. Bunyi bel panti menghentikan aktivitas ini; pertanda waktu makan siang tiba.
“Ayo Oma-oma, kita sudahi dulu ya…. Lusa, kita lanjutkan lagi,” ucapku menyodorkan janji.
Para oma lekas mengemasi gulungan benang, haakpen, dan gunting masing-masing. Dua oma tampak memunguti potongan-potongan benang yang terserak di lantai. Sementara Oma Lanti masih terbenam dalam kenikmatan merajut. Rasa penasarannya sanggup menaklukkan lapar. Betapa pada usia lanjut, oma-oma ini masih ingin menorehkan makna.
Dua tahun sudah kulintasi waktu di panti werdha ini. Waktu bergulir tiada berirama. Jatuh bangun kucoba melupakan untaian masa lalu. Keberhasilan yang pernah diraih, pada akhirnya hanya menjadi kenangan atau sekadar jejak yang terbengkalai dalam lumbung ingatan. Menjadi tua kerap merupakan tragedi. Dan, kini, kutiti pematang tragediku…
*****
Masuk panti werdha merupakan sebuah keputusan yang panjang dan berkelok. Kusadari, kebebasanku bakal terenggut. Aku tak leluasa lagi berkegiatan.
Padahal kondisiku bukan tak berdaya. Aku bukan tidak punya apa-apa. Pun bukan sebatang kara. Rumahku masih berdiri cukup megah di sebuah kawasan nan bersih di emper Ibu Kota.
Suamiku berpulang tatkala tubuhku belum renta. Seiring bergulirnya waktu, si sulung Ruben bersulang kasih dengan dara berbeda bangsa. Itu berarti, aku “kehilangan” dia. Tak bisa lagi sewaktuwaktu aku bertatap muka dengan putra kebanggaanku.
Sementara aku tinggal dengan si bungsu Cici di rumah peninggalan suami. Gilirannya pun tiba, Cici melepas masa lajang.
“Tetaplah tinggal di sini bersama Mama, Ci. Rumah ini terlalu besar untuk Mama tinggali sendirian,” pintaku.
Nyatanya, tinggal bersama Cici tak lagi seperti dulu. Perlahan-lahan waktu mengubah perangainya. Kesibukan mengepungnya. Sepanjang hari ia mencari nafkah. Sepulang kerja, ia bercengkerama dengan sang suami. Waktu yang tersisa untukku sekadar untuk basa-basi.
“Mama sudah makan?” Itu kalimat yang terluncur dari mulutnya setiap kali kami berjumpa mendekati pengujung hari.
Setelah cucu-cucu lahir, gesekan friksi kerap menelentang terang benderang.
“Mama terlalu memanjakan cucu!” Robert, menantuku, meluncurkan protes.
Untuk memangkas campur tangan terhadap keluarga putriku, aku banyak berkegiatan di luar rumah. Beberapa kegiatan rohani, kuikuti. Juga kegiatan bermasyarakat dalam lingkup RT dan RW kulakukan. Segala undangan reuni kuhadiri, dari teman-teman semasa SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Semua itu membuat aku gembira kendati hanya sesaat…
Sewaktu kembali ke rumah, sepi masih menyelinap. Sepi itu sanggup meluruhkan makna masa senjaku. Hingga akhirnya, kudapati jiwaku hampa. Lalu, keinginan masuk panti werdha muncul.
“Mama ingin masuk panti,” ucapku kepada Cici.
“Mama sudah tidak betah lagi ya tinggal di rumah ini?” balas Cici menggali alasanku.
“Mama sering kesepian,” beberku terus terang.
“Kesepian itu penyakit kebanyakan lansia, Ma,” dalih Cici yang tak hendak kugubris.
Hari demi hari terus berkejaran. Masalah baru muncul dalam diriku. Benakku mulai digerogoti demensia.
“Mama lupa lagi mematikan kompor. Bahaya banget, Ma!” pekik Cici tanpa mengontrol lengkingan suaranya.
“Oooo… Mama tidak ingat menyalakan kompor,” kilahku.
Selang beberapa waktu, Cici sempat memberondongku dengan omelan sebelum ia berangkat kerja.
“Mama tidak mematikan keran wastafel. Kamar mandi banjir tuh!” keluh Cici melebih-lebihkan.
Tak jarang, Cici mengoceh jika aku menanyakan sesuatu. Tanpa kusadari, ternyata sudah berkali-kali aku melontarkan pertanyaan serupa.
“Ya ampuuunnn, Ma! Ini pertanyaan kedelapan, Ma. Kalau aku jawab, diingat-ingat dong Ma! Jangan tanya-tanya melulu. Capek deh,” kata Cici dengan nada separuh menghardik.
Meski aku semakin mudah lupa, ada satu hal yang masih kuingat dengan jernih, yakni keinginan masuk panti werdha.
“Lebih enak Mama menghabiskan masa tua di panti jompo,” kataku mengulangi permintaan yang pernah kulontarkan beberapa pekan sebelumnya.
Akhirnya, kesempatan itu datang. Setelah masuk waiting list selama beberapa bulan, ada kamar kosong untukku di sebuah panti werdha yang lokasinya agak jauh dari kebisingan kota.
*****
Nyatanya, hidup di panti werdha tak memungkasi persoalan. Serangkaian masalah tetap hilir-mudik di kepalaku. Suasana panti werdha cenderung berisik bagiku. Sebagian opa dan oma masih doyan bicara, terlebih tentang masa lalu mereka. Anehnya, tetap ada sunyi di antara cerocos sosok-sosok lansia itu.
Bila benakku penat, aku memojok di pekarangan panti. Kuhirup energi dari aneka pepohonan yang tumbuh kokoh di situ. Tanaman-tanaman ini mengguratkan teladan ketegaran. Sejatinya, badai persoalan justru mengokohkan akar kepribadian.
Kutepis kecewa dan sesal yang sempat menyinggahi hati. Kucoba melumat keheningan yang tersisa di tempat ini. Lantas, kuciptakan suasana meditatif. Pada saat-saat demikian, aku merasakan tubuhku homeostatis; produksi hormon melantonin dan endorfin yang menenteramkan melesat tajam, mengendalikan jiwa…
Selanjutnya, batinku dipenuhi syukur. Aku menerima kondisi uzur ini. Aku menerima bahwa perlahan-lahan sosokku mulai terlupakan. Bahkan Cici dan anak-anaknya jarang mengunjungi aku lagi.
Kunikmati embusan angin yang membelai helai-helai rambutku, yang telah keperakan diwarnai sang waktu. Sekali lagi, kubersyukur karena aku masih sehat meski gerak tubuhku mulai tersendat.
Tatkala ayunan kakiku mencapai gerbang panti, tampak ada penghuni baru. Kubelalakkan manik mataku ingin tahu. Mendadak aku dijerat peranjat. Jantungku terasa lebih cepat berdetak.
Alamaaak! Kendati rambut di kepala orang itu telah menipis dan ukuran tubuhnya mulai melar mendekati tambun, aku langsung bisa mengenalinya. Di keremangan petang, kudapati sosok Arman. Orang itu pernah mengisi ceruk hatiku semasa kami teramat belia, tatkala rambutnya tebal menyentuh bahu, tatkala ketampanannya sanggup menggiurkan aku.
“Maria… kamu tinggal di sini?” sapa Arman dengan ekspresi kaget.
“Iya..,” kataku tergeragap seraya menata perasaan yang tiba-tiba tak keruan. Kusambut jabat tangannya yang hangat dengan selarik senyum.
Apakah ini tragedi atau berkat, entahlah! Malam itu, penantianku menjelang pulang -–menghadap Sang Khalik-tak lagi sunyi.
Puspita Loka, 6 November 2019
Maria Etty
HIDUP NO.48 2019, 1 Desember 2019