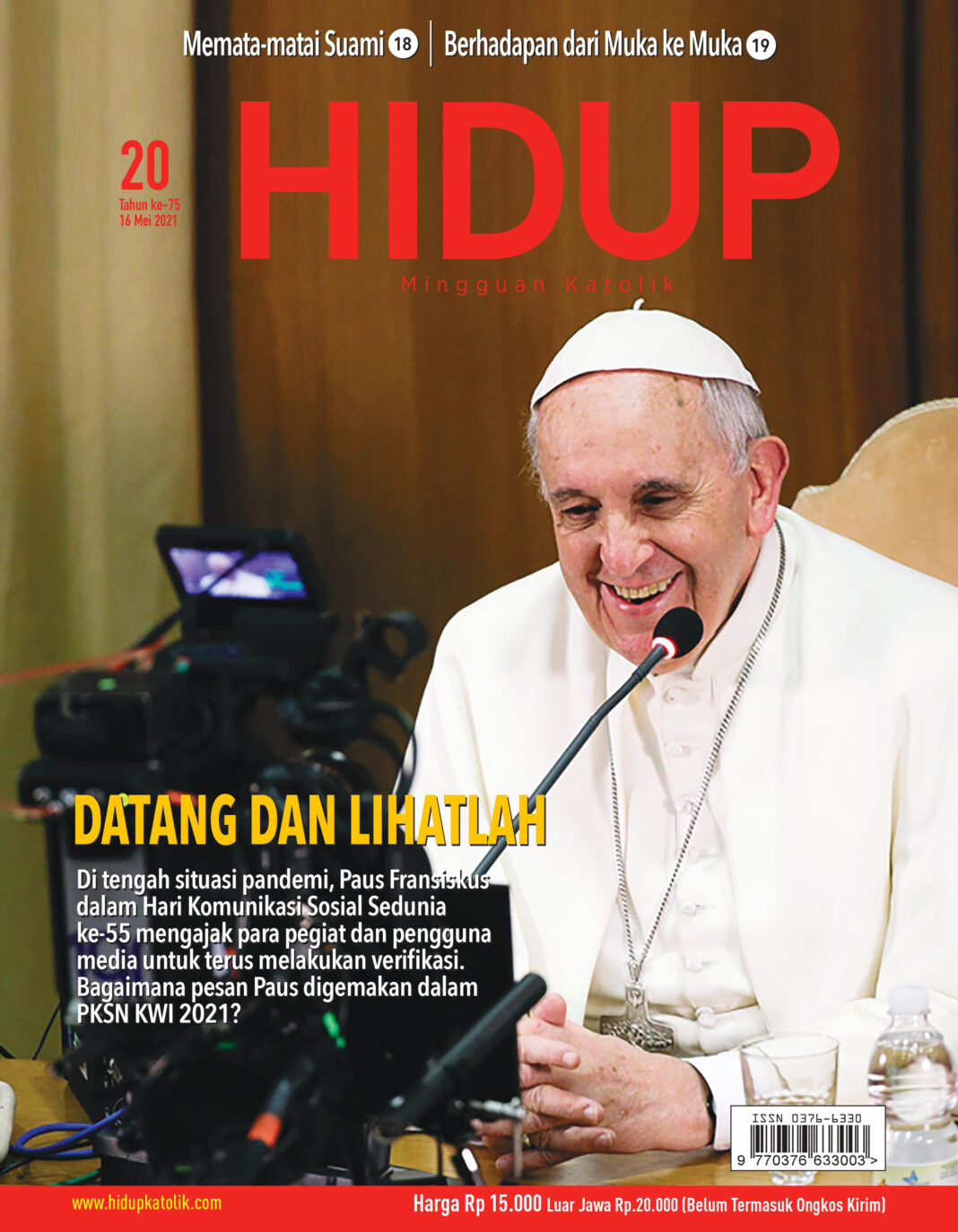HIDUPKATOLIK.COM – HANS Küng, teolog kontroversial itu wafat hampir bersamaan dengan bencana badai Seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT). Wafatnya 175 orang dan hilangnya 45 orang menjadi sebuah duka mendalam. Kemiskinan yang menjadi ciri teritorial NTT yang membuat ‘Nasibnya Tak Tentu’ kini diperparah oleh badai Seroja.
Sebagai bencana alam, tentu ia tidak punya kaitan lansung dengan perbuatan manusia secara kasat mata sebagai sebabnya. Dalam refleksi teologis ‘sekenanya’ memang kerap dibaca secara sederhana seperti itu. Bencana kini adalah akumulasi sebab yang ada jauh ada sebelumnya.
Yang jadi pertanyaan: mengapa di dua daerah Amakaka (Lembata) dan Nelelamadike (Adonara) mendapatkan konsekuensi terparah? Pertanyaan ini akan dengan serta merta membuka mata bahwa keterlibatan manusia tidak bisa dilepasakn begitu saja. Jelasnya, alam semestinya memiliki mekanisme untuk melindungi manusia apabila hadir goncangan dahsyat. Namun, manusia oleh terlampau mengutamakan rasionalitas mengingkari seruan alam.
Kesadaran seperti ini telah menjadi kegalauan teologis yang didengungkan Hans Küng hampir 40 tahun lalu. Figur kelahiran Sursee, Swiss, 19 Maret 1928 yang wafat dua hari setelah badai Seroja telah berulang mengungkapkan tentang peran agama dalam membangun etika global agar bahaya pertumbahan daerah baik perang maupun dampak ekologis dapat terhindarkan.
Yang terjadi justru sebaliknya. Masih terdapat apa yang disebut sebagai patologi modernitas. Demi mengejar kemajuan, pembunuhan dan kematian jutaan manusia akibat perang, pembunuhan, kemiskinan, dan kelaparan serta kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pada konteks bencana di NTT (khususnya Amakaka dan Nelelamadike, aspek kerusakan alam menjadi sebab terdekat yang tentu tidak bisa dihindari begitu saja.
Tentu tidak elok ketika masih dalam duka, para korban dipersalahkan. Yang harus diakui, mereka bisa saja menjadi korban dari persaingan yang oleh Scott Lash disebut sebagai estetikanisasi kehidupan. Mereka terdepak dari persaingan global dan tidak ada pilihan selain kembali memanfaatkan setiap jengkal tanah yang masih bisa digunakan demi bertahan hidup.
Dalam bukunya Global Responsibility In Research of a New Worl Ethic, 1991, Küng melihat titik temu pada agama-agama. Baginya, keyakinan pada the Ultimate Reality atau Tuhan diyakini bisa memberikan motivasi moral tingkat paksaan (compulsion) sehingga jadi modal bagi agama-agama membentuk etika yang sama.
Pada konteks bencana yang melanda NTT yang merupakan mayoritas Kristen atau secara khusus kalau melihat daerah terparah di Adonara dan Lembata, yang merupakan wilayah Katolik maka panggilan akan sebuah aktualisasi teologi ekologi merupakan keharusan. Gereja perlu memainkan peranan penting baik menggugah kesadaran moral maupun secara kompulsif ikut dalam gerakan ekologis.
Keuskupan Larantuka, misalnya telah menetapkan 2017 sebagai tahun ekologis. Namun dampak yang kini terasa menyadarkan bahwa gerakan itu belum memiliki dampak berarti. Jelasnya, meskipun Mgr. Frans Kopong Kung di depan Muspida Flotim sudah menekankan tentang bumi sebagai ibu, rumah, dan saudari tetapi gerakan itu masih sebatas seruan dan belum menjadi program kualitatif yang berdampak.
Lebih jauh, apa yang terjadi di NTT tidak bersifat tunggal. Ia mengingatkan kita akan Anthony Giddens. Dalam bukunya The Consequence of Modernity, 1990, ia ingatkan bahwa masalah ini bersifat transnasional. Ia telah melampaui ruang dan waktu. Buktinya badai yang biasa melandai Australia kini sudah menyeberang ke NTT.
Yang lebih dikuatirkan hal mana menjadi kegalauan Hans Küng, dunia yang kian mengglobal akan mudah menghadirkan permasalahan ekonomi dan budaya secara nyata dan terjadi kapan dan di mana saja. Di sini komitmen agama menjadi sangat kuat. Agama tidak bisa lagi membedakan ruang gerak hanya kepada ‘rohani’. Agama tidak tinggal dalam dunia Patonik. Ia juga menggapai manusia dengan daging dan darah.
Hal ini menghadirkan imperatif bahwa di tengah bencana, institusi Gereja perlu lebih menyerajarah yang berjuang bersama perubahan dan kefanaan. Ia perlu ikut terlibat mewujudkan serta menyelesaikan krisis dan keprihatinan umatnya.
“Agama tidak bisa lagi membedakan ruang gerak hanya kepada ‘rohani’.”

Robert Bala, Pemerhati Teologi Ekologi