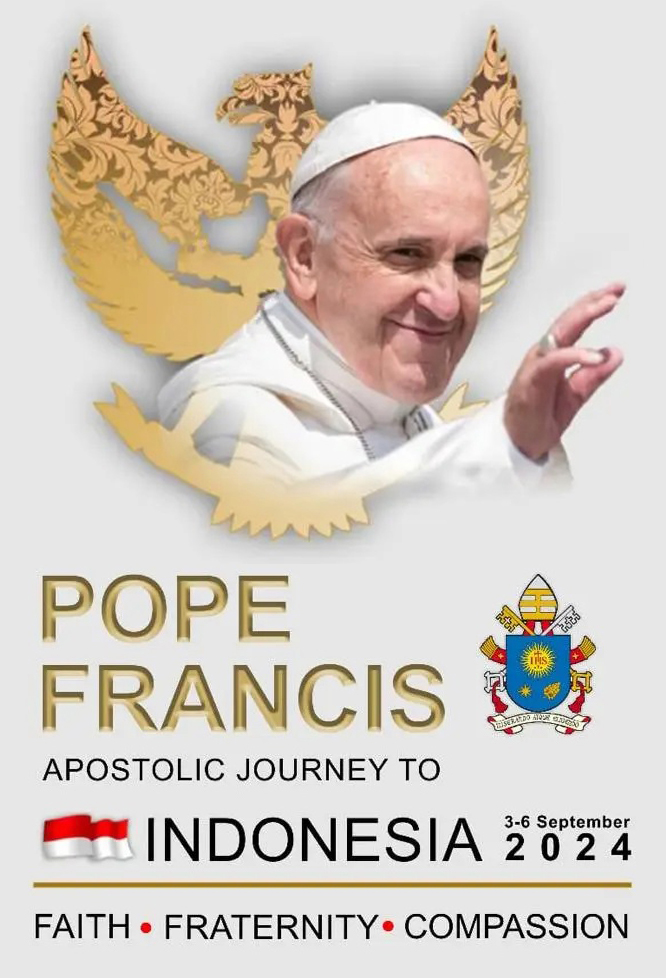HIDUPKATOLIK.COM – Pendidikan sangat penting bagi sebuah bangsa. Plato bahkan menegaskan bahwa pendidikan menyumbang begitu besar bagi terciptanya kualitas sebuah negara. Baginya, pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan warga negara yang berkualitas.
Penegasan Plato ini diamini pula oleh orang Batak Toba sebagaimana terungkap dalam lagu Nahum Situmorang, pencipta lagu legendaris Batak Toba. “Hugogo pe mancari, arian nang bodari, lao pasikkolahon gelleng hi. Naingkon do singkola, satimbo-timbu na, sikkap di na tolap gogo hi”. – Saya akan bekerja sekuat tenaga mencari nafkah, siang dan malam untuk menyekolahkan anak-anakku. Mereka harus sekolah setinggi-tingginya, selagi maasih berdaya ” demikian ungkapan Nahum Situmorang dalam penggalan lirik lagu “Anakhon Hi Do Hamoran Di Ahu”.
Penting Berpikir Kritis
Pertanyaan mendasar: Model pendidikan sepertia apa yang perlu dihidupkan agar sebuah negara bermutu, termasuk republik ini? Cukup banyak pemikir menjawab pertanyaan ini. Salah satu di antaranya adalah Paulo Freire. Dalam bukunya The Politics of Education: Culture, Power, and Liberation (1985), Paulo Freire menyatakan bahwa hal penting dalam pendidikan adalah membangkitkan kesadaran peserta didik tentang dirinya, lingkungannya, dan sesamnya, artinya memiliki kepekaan terhadap dunia yang dihidupinya.
Kepekaan akan realitas itu terjadi ketika pola pikir kritis diberi ruang luas. Pola pikir ini mendorong peserta didik dan guru mencermati, bertanya, dan menggugat. Artinya, proses pembelajaran tidak pada tempatnya hanya mengulang-ulang kalimat yang tampak tidak masuk akal, tidak cukup pula hanya berteori belaka. Pendidikan akan lebih berhasil jika tidak terlalu teoritis, dan tidak hanya praktis tanpa isi, tetapi menggugah, bertanya dan mencermati.
Menghidupkan pola pikir kritis berarti menjadikan para anak didik pelaku (subjek) yang bebas, pencipta yang kreatif, dan penggagas segudang ide. Di sana ingin tahunya secara berkelanjutan digugah. Di sana juga ada suasana dan hubungan dialektis antara guru dan peserta didik, dan yang tidak kalah penting, terbentuk sikap rendah hati dalam sanubari para anak didiknya. Jadi, belajar adalah menciptakan dan merekonstrukan ide, bukan menghafal dan mereproduksinya.
Peran Penting Filsafat
Pertanyaan selanjutnya adalah: matakuliah atau pola berpikir seperti apa menjadi wadah bagi kebangkitan pola pikir kritis itu? Jika kita berkaca dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, jawaban atas pertanyaan ini jelas ada pada kata “Filsafat”. Dalam beberapa literatur filsafat, di sana ditegaskan bahwa salah satu ciri dari ciri filsafat adalah berpikir kritis.
Franz Magnis Suseno misalnya sangat eksplisit menunjukkan hal itu dalam bukunya berjudul Filsafat sebagai Ilmu Kritis (1991). Bagi Magnis filsafat kritis, termasuk terhadap dirinya merupakan ciri utama. Filsafat terus mencari jawaban, tidak puas terhadap diri sendiri, dan tidak membiarkan segalanya sudah selesai. Intinya, filsafat menjadi ilmu kritis.
Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Paulo Freire, tokoh pendidikan Brazil. Freire menegaskan tentang kedudukan berpikir kritis dalam pendidikan. Menurutnya, berpikir dan sikap kritis memiliki peran penting dalam pendidikan karena menempatkan pendidikan sebagai aksi budaya yang membebaskan. Dalam hal ini filsafat memberikan sumbangan penting tumbuhnya sikap itu. Filsafat menyediakan prinsip-prinsip tindakan bagi kesadaran kritis dan memberi landasan bagi proklamasi realitas baru. Tanpa filsafat alih-alih mengancam realitas, ia justru akan jatuh ke dalam mistifikasi pengetahuan ideologis (“the mystifications of ideological knowledge”).
Dengan Filsafat, pendidikan sebagai aksi budaya dominasi menjinakkan disingkirkan. Aksi utamanya justru membuka ruang dialog, yang tujuannya membangun kesadaran kritis peserta didik, mengungkap realitas dan kedok-kedok ideologi yang bercokol di masyarakat, bukan menyebarkan slogan-slogan dan menjadi strategi untuk menguasi orang lain dan mempertahankan “status quo”. Pola demikian menjadikan pendidikan sebagai aksi humanisasi dan hominisasi, meminjam istilah Nikolas Driyarkara, SJ, filsuf Indonesia.
Lebih lanjut Paulo Freire mengamini bahwa bengan filsafat, ada ajakan untuk secara kritis mengenali dan membuka tabir realitas, menghindari penanaman kesadaran palsu dan adaptasi diri yang serba kilat terhadap kenyataan yang ada (membeo) dan menolak dikotomi subjek (guru) dan objek (murid).Model pendidikan sebagai yang membebaskan diistilahkan Paulo Freire dengan konsientisasi (“consientization”), yakni proses di mana peserta didik berpartisipasi secara kritis dalam tindakan yang mengubah.
Dengan konsientisasi, peserta didik menggugah dirinya untuk melakukan sesuatu positif bagi kemajuan bangsa dan negaranya, dan tentu tidak kalah penting, mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan sesamanya. Dengan konsientisasi pula, pendidikan menjadi aksi humanisasi: menyadarkan peserta dididik keluar dari kungkungan berbagai hal: kemiskinan, kebodohannya, dan daya yang mengeksploitasi dan mengalienasi. Inilah yang menghasilkan warga negara yang bermutu seperti dicita-citakan oleh Plato.
Hantu Scopus di Perguruan TInggi
Apa yang ditegaskan oleh Franz Magnis Suseno dan Paulo Freire berintikan hal yang sama yakni pentingnya menghidupkan sikap kritis dalam pendidikan. Menyongsong sekaligus memaknai perayaan 80 tahun Kemerdekaan Indonesia tahun 2025 ini pertanyaan kita: Apakah dunia pendidikan di negeri ini sungguh membebaskan pelaku pendidikan: guru, dosen dan peserta didik? Atau justru pendidikan menjadi ajang menjinakkan? Menurut hemat saya, esensi situasi pendidikan republik ini masih mirip dengan kondisi saat Paulo Freire mengeluarkan gagasan konsientisasi ini. Yang berbeda hanya bentuknya. Bagaimana itu terungkap?
Sebagai pegiat pendidikan di perguruan tinggi (dosen), itu sangat kentara dengan penempatan Scopus sebagai persyaratan pengurusan jabatan akademik dan ukuran mutu dosen. Menurut saya kebijakan ini menjadi cermin pendidikan sebagai upaya penjinakan, bahkan lebih parah, tanpa disadari, aksi eksploitasi berlipat-lipat, dan alienasi. Logikanya sederhana: Penulis (para dosen) sudah menghabiskan tenaga dan pikirannya saat meneliti hingga merangkai hasil penelitiannya dalam tulisan. Lalu untuk dimuat di jurnal internasional terindeks Scopus, penulis harus membayar dengan harga jutaan, bahkan puluhan juta, tergantung tingkat Q-nya. Setelah dimuat di jurnal berindex Scopus itu, karya itu menjadi milik dari pengelola jurnal di luar sana (orang asing). Ketika penulisnya mau mengakses jurnal itu, ia harus bayar lagi.
Jadi, dosen/peneliti harus membayar karyanya sendiri untuk menjadi milik orang lain, lalu ketika ia ingin membuka jurnalnya, ia harus membayarnya. Sesuatu yang tidak masuk akal dari sisi makna pendidikan dan sisi ekonomis. Kondisi demikian jelas tidak hanya merupakan sebuah upaya nyata menjinakkan, tapi juga mengeksploitasi dosen secara berlapis-lapis, bahkan mengalienasi dosen dari karyanya sendiri, persis seperti situasi buruh, sebagaimana ditegaskan oleh Karl Marx dalam Das Kapital (1867). Meminjam pemikiran Armada Riyanto, ini merupakan kolonialisme baru, yang perlu dilawan sebagaimana ditunjukkan dalam buku Dekolonisasi: Filsafat – Metodologis, Kesadaran tentang Liyan, kekuasaan, dan Societas “Kita” (2025).
Lebih menyedihkan, dan konyol, pembuat kebijakan pendidikan tinggi di negeri ini mengikuti selera pengelola jurnal-jurnal Scopus, yang tidak lain adalah kaum kapitalis fsm menjadikan itu sebagai dasar kebijakan dalam penilaian Indeks Kinerja Utama (IKU) dosen dan urusan jabatan akademik selama berpuluh-puluh tahun. Para dosenpun, termasuk bergelar guru besar, ikut manut dengan penjinakan itu demi prestise dan jabatan akademik, bahkan menjadikannya ladang bisnis. Jadi pengambil kebijakan ikut secara terstruktur menjadikan pendidikan sebagai aksi budaya dominasi, bukan aksi budaya untuk kebebasan.
Berkaca dari makna pendidikan kritis seperti ditegaskan oleh Franz Magnis Suseno dan Paulo Freire, nampaknya sudah saatnya pendidikan di negari ini sungguh-sungguh menjadikan sepua peserta didik dan pendidik sebagai subjek otonom dan mandiri dari kungkungan pola pikir bisnis, dominasi dari orang asing, lebih-lebih kesadaran ini dimiliki secara absolut oleh pengambil kebijakan di bidang pendidikan.
Secara lain dapat dikatakan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan, khususnya pendidikan tinggi menyadari bahwa upaya kapitalisme yang menjinakkan, mengeksploitasi, bahkan mengalienasi dosen dari karyanya itu masih marak dan membahayakan bagi kemajuan pendidikan di negeri ini. Singkatnya, bangsa ini harus berani melawan kapitalisasi ilmu pengetahuan dan kapitalisasi proses urusan jabatan akademik dengan label “hantu” Scopus itu dengan mengeleminir kebijakan yang memuat hantu Scopus sebagai persyaratan penilaian dan kenaikan jenjang akademik. Indonesia adalah bangsa besar. Di usia 80 tahun saatnya bangsa ini menunjukkan kemandirian dan otonomi moralnya dalam menentukan kualifikasi pendidikan negaranya, tidak mau disetir oleh orang asing, lebih-lebih pelaku bisnis. Semoga

Kasdin Sihotang
Dosen Filsafat Moral di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta